Saparuddin
Sanusi
Mahasiswa
Sastra Inggris Fakultas Sastra Unhas
Pengetahuan
lokal merupakan istilah yang problematik (Nygren:1999). Pengetahuan lokal
dianggap tidak ilmiah, sehingga pengetahuan lokal tersebut dibedakan dengan
pengetahuan ilmiah yang dikenalkan oleh dunia barat. Titik temu antara
pengetahuan local yang tidak ilmiah dan yang ilmiah tersebut keduanya berada
pada bagaimana cara memahami dunia mereka sendiri. Pengetahuan local dapat
ditelusuri dalam bentuk pragmatis maupun supranatural. Pengetahuan dalam
bentuk pragmatis menyangkut pengetahuan tentang kaitan pemanfaatan sumberdaya
alam, dan dalam bentuk supranatural, ketika pengetahuan itu menjadi
seolah-olah tidak ilmiah (unreason). Untuk yang pragmatis ini, pengetahuannya
berubah, karena berhubungan dengan pihak lain dari wilayahnya. Pengetahuan
lokal selalu dianggap sebagai lawan dari pengetahuan barat yang bersifat ilmiah,
universal, memiliki metodologi dan dapat diverifikasi. Pengetahuan lokal
dianggap bersifat lokal, terbatas dan tidak memiliki metodologi dan sebagainya.
Pembedaan ini secara tidak sadar memelihara perbedaan antara pengetahuan ilmiah
negara barat dan pengetahuan lokal (negara timur), yang pada akhirnya
memelihara pandangan kolonialisme antara barat dan timur.
Menurut Wietoler (2007), masyarakat dengan pengetahuan dan kearifan lokal telah
ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah
sam-pai sekarang ini, kearifan tersebut merupakan perilaku positif manusia
dalam berhu-bungan dengan alam dan lingkungan seki-tarnya yang dapat bersumber
dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat
yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk
beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi
suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun,
secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang
berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa
yang tinggal di daerah itu.
Manusia
harus memperlakukan lingkungan di sekitarnya sebagai tempat tinggal yang telah
memberikan segalanya untuk kita, sehingga ada tanggung jawab yang besar untuk
menjaga dan mengelolanya, pengembangan teknologi sederhana di dalam mengelola
sumberdayanya akan selalu dipertahankan untuk menjaga tradisi, memberi motivasi
dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola wilayahnya sehingga peran
masyarakat sebagai kunci utama dalam menjaga keseimbangan sumberdaya alam yang
ada di sekitarnya. Kearifan lokal harus menjadi yang terdepan dalam menjalankan
program-program pengembangan wilayah di kawasan kars untuk mendorong masyarakat
sebagai pelaku utama dalam usaha mengembangkan sumberdaya alamnya.
Kalau kita
menengok ke belakang saat kita belum punya teknologi, bagaimana cara bertahan
hidup bangsa Indonesia pada zaman dahulu dalam menghadapi bencana? ada berapa
contoh kearifan lokal yang telah menyelamatkan banyak orang akan tetapi jarang
diketahui orang. Kearifan lokal ini berkembang karena selama ratusan tahun
secara geologi, klimatologis, geografi dan kondisi sosial demografi Indonesia
rawan bencana gempa, tsunami, gunung api, longsor, rawan banjir, angin ribut,
keke-ringan, kebakaran hutan, konflik sosial, penyakit menular dan lain
sebagainya. Dalam perkembangannya kearifan lokal mulai
terpojokkan/terpinggirkan dikarena-kan datangnya ilmu pengetahuan dari barat.
Hal ini terjadi karena kearifan lokal tidak punya bukti ilmiah yang bisa
diterima secara rasional.
Dalam kaitan
itu, pada masyarakat adat ini dikenal adanya pembagian kawasan, yaitu pertama,
kawasan untuk budidaya untuk dinikmati bersama; kedua, kawasan hutan kemasyarakatan
yang setiap warga diperbolehkan menebang pohon, tetapi harus terlebih dahulu
menanam pohon pengganti; dan ketiga, kawasan hutan adat (borong karamaq) yang
sama sekali tidak boleh dirambah (Basri Andang, 2006). Pelanggaran terhadap
ketentuan adat ini akan dijatuhi sanksi adat, dalam bentuk pangkal cambuk atau
denda uang dalam jumlah tertentu, sesuai dengan ada’ tanayya, sebuah sistem
peradilan adat Kajang. Mereka juga memiliki lembaga adat yang disebut dengan tau limayya (organisasi yang beranggotakan
lima orang), dipimpin oleh seseorang yang bergelar ammatowa, yang tugas
utamanya mengatur penebangan pohon, pengambilan rotan, dan pemanenan lebah madu
di hutan adat, serta penangkapan udang.
Kearifan
masyarakat adat Kajang dalam mengelola sumber daya alamnya memang
diartikulasikan lewat media-media tradisional seperti mitos, ritual, dan
pesan-pesan leluhur, tetapi sesungguhnya me-ngandung pengetahuan ekologis,
yaitu sistem pengetahuan mengenai fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem.
Bahkan uraian di atas memperlihatkan empat elemen kearifan lingkungan, yaitu
sistem ni-lai, teknologi, dan lembaga adat. Tidak hanya pada masyarakat adat
Kajang, di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah masyarakat lokal yang memiliki
kearifan lingkungan, seperti lontaraq (kitab) Sawitto yang menyimpan
pengetahuan tentang cara me-motong pohon untuk tiang rumah, dan per-lunya
mengganti pohon yang ditebang dengan pohon baru; peran lembaga adat uwaq atau
uwattaq pada masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam
mengontrol pemanfaatan sumber daya alam; peran ritual dan aluk pada orang
Toraja yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang; upacara macceraq
tasiq (membersihkan laut) yang pernah dipraktikkan oleh orang Luwu di masa
lalu; dan lain-lain.
Dalam kaitan
dengan upaya konservasi atau pengembangan sistem pengelolaan lingkungan yang
berkelan-jutan, bentuk-bentuk kearifan lingkungan sebagaimana dikemukakan ini
menjadi penting dan dapat disinergikan dengan sistem pengetahuan modern. Hal
ini juga telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup bahwa aspek perilaku manusia merupakan bagian yang integral
dalam pengelolaan lingkungan hidup. Contoh konservasi yang menarik dikemukakan
adalah inisiatif masyarakat dalam penghijauan bakau di Tongke-tongke, pesisir
Timur Kabupaten Sinjai pada paruh awal tahun 1990-an (Robinson & Paeni,
2005). Penanaman bakau ini dimaksudkan untuk melindungi kampung dan tambak masyarakat
setempat dari abrasi. Mereka membuat aturan penebangan pohon yang dilakukan dalam
siklus tujuh tahunan. Usaha ini melahirkan dampak ekonomis, di mana penduduk
dapat memperoleh tambahan pendapatan ekonomi keluarga dengan mengumpulkan
akar-akar bakau yang sudah mati untuk kebutuhan kayu bakar rumah tangga. Namun,
belakangan usaha ini melahirkan konflik yang melibatkan masyarakat menyangkut
status kepemilikan antar Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai yang memiliki
otoritas untuk mengatur penebangan, dan Dinas Perikanan yang memiliki wewenang
menebang bakau untuk dijadikan tambak.
Proses
pengelolaan lingkungan ada baiknya dilakukan dengan lebih meman-dang situasi
dan kondisi lokal agar pende-katan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan
kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan ini tampaknya relevan untuk
dilaksanakan di Indonesia dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan
kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki
perbedaan disamping kesamaan. Dengan demikian, strategi pengelolaan pada
masing-masing wilayah akan berva-riasi sesuai dengan situasi setempat.
Yangperlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh
suatu masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan.
Melalui pasang,
masyarakat Ammatoa menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen
dari suatu sistem yang saling terkait secara sistemis; Turiek Akrakna (Tuhan),
Pasang, Ammatoa (leluhur pertama), dan tanah yang telah diberikan
oleh Turiek Akrakna kepada leluhur mereka. Merawat hutan, bagi
masyarakat Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan
merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh Turiek Akrakna kepada
leluhur Suku Kajang. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan
gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak
dijaga kelestariannya. Kekuatan itu berasal dari arwah leluhur masyarakat
Kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat
jahat manusia (Aziz, 2008). Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan,
misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah
para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan itu dapat berupa
penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga dapat
mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan Tanatoa
Kajang. Tentang hal ini, sebuah pasang menjelaskan:
Naparanakkang
juku
Napaloliko
raung kaju
Nahambangiko
allo
Nabatuiko
Ere Bosi
Napalolo’rang
Ere Tua
Nakajariangko
Tinanang
Artinya:
Ikan bersibak
Pohon-pohon bersemi,
Matahari bersinar,
Hujan turun,
Air Tuak menetes,
Segala tanaman menjadi (Adhan, 2005: 262).
Pasang di atas
merupakan gambaran bagaimana masyarakat Kajang menghormati lingkungannya dengan
cara menjaga hutan agar tetap lestari. Bagi orang Kajang, tetap terjaganya
kelestarian hutan juga merupakan petanda bahwa Ammatoa yang terpilih
diterima oleh Turiek Akrakna dan alam. Ammatoa dianggap telah
berhasil mengimplementasikan ajaran-jaran pasang sebagaimana dititahkan
oleh Turiek Akrakna. Terlepas dari benar-salahnya ajaran yang diyakini
masyarakat Kajang, yang pasti konstruksi mereka tentang hutan yang bersifat
sakral tersebut tidak dapat disangkal telah berperan besar dalam menjaga tetap
lestarinya kawasan hutan mereka.
Berbicara
tentang kearifan ekologis yang dipraktekkan oleh masyarakat Kajang, kita tidak
dapat melepaskannya dari sebuah prinsip hidup yang disebut tallase
kamase-mase, bagian dari pasang yang secara eksplisit memerintahkan
masyarakat Kajang untuk hidup secara sederhana dan bersahaja. Secara harfiah, tallase
kamase-mase berarti hidup memelas, hidup apa adanya. Memelas, dalam arti
bahwa tujuan hidup warga masyarakat Kajang menurut pasang adalah
semata-mata mengabdi kepada Turek Akrakna. Prinsip tallase
kamase-mase, berarti tidak mempunyai keinginan yang berlebih dalam
kehidupan sehari-hari, baik untuk makan, maupun dalam kebutuhan pakaiannya.
Dengan cara yang demikian, maka keinginan mendapatkan hasil berlebihan dari
dalam hutan dapat dihindari, setidak-tidaknya dapat ditekan seminimal
mungkin, sehingga hutan tidak terganggu kelestariannya (Salle, 2000).
Hidup
sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang berfungsi sebagai
pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara lebih
jelas tallase kamase-mase ini tercermin dalam pasang sebagai
berikut:
1.
Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase,
a’dakkako nu kamase-mase, a’meako nu kamase-mase artinya; berdiri engkau sederhana,
duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau
sederhana.
2.
Anre
kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre na rie, care-care na rie,
pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju. Artinya;
Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya,
pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya
(Restu dan Sinohadji, 2008).
3.
Jagai lino lollong bonena, kammayatompa langika, rupa
taua siagang boronga. Artinya; Peliharalah dunia beserta isinya, demikian
pula langit, manusia dan hutan.
Pasang ini mengajarkan nilai kebersahajaan
bagi seluruh warga masyarakat Kajang, tak terkecuali Ammatoa, pemimpin
tertinggi adat Kajang. Hal ini dapat dipandang sebagai filosofi hidup mereka
yang menempatkan langit, dunia, manusia dan hutan, sebagai satu kesatuan yang
tak terpisahkan dalam suatu ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya.
Manusia hanyalah salah satu komponen dari makro kosmos yang selalu tergantung
dengan komponen lainnya. Untuk itu, dalam berinteraksi dengan komponen makro
kosmos lainnya, manusia tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena akan
merusak keseimbangan yang telah tertata secara alami (Salle, 2000).
Masyarakat
adat Kajang sangat konsisten memegang teguh prinsip tallase kamase-mase
ini. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka mengimplementasikannya dalam
praktek hidup sehari-hari sebagai berikut:
- Bentuk rumah yang seragam, seragam bahannya, seragam besarnya, dan sedapat mungkin seragam arah bangunannya. Keseragaman itu bermaksud menghindari saling iri di kalangan mereka, yang dapat berakibat pada keinginan memperoleh hasil lebih banyak dengan cara merusak hutan.
- Larangan membangun rumah dengan bahan bakunya batu-bata. Menurut pasang, hal ini adalah pantangan, karena hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh tanah. Rumah yang bahan bakunya berasal dari batu-bata, meskipun penghuninya masih hidup namun secara prinsip mereka dianggap sudah mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah. Apabila diperhatikan hal tersebut lebih jauh, maka sebenarnya pantangan yang demikian bersangkut-paut dengan pelestarian hutan. Bukankah untuk membuat batu-bata, diperlukan bahan bakar kayu, karena proses pembakaran batu-bata memerlukan kayu bakar yang cukup banyak. Dengan pantangan itu sebenarnya memberikan perlindungan pada bahan bakar kayu yang sumber utamanya berasal dari hutan.
- Memakai pakaian yang berwarna hitam. Warna hitam untuk pakaian (baju, sarung) adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Menurut pasang, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Turek Akrakna. Kesamaan bukan hanya dalam wujud lahir, akan tetapi juga dalam menyikapi keadaan lingkungan, utamanya hutan mereka, sehingga dengan kesederhanaan yang demikian, tidak memungkinkan memikirkan memperoleh sesuatu yang berlebih dari dalam hutan mereka. Dengan demikian hutan akan tetap terjaga kelestariannya (Salle, 2000).
Untuk
memenuhi kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya
alam di sekitar mereka, masyarakat adat Kajang dengan demikian bukanlah
masyarakat yang mengejar kekayaan material, namun mengejar kehidupan abadi di
akhirat. Karena itu, bagi mereka, tanah bukan untuk dieksploitasi demi materi,
melainkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup secukupnya. Dari penjelasan
tersebut, tallase kamasa-mase juga merupakan representasi dari tiga
prinsip utama. Pertama, perbuatan manusia di dunia akan mempengaruhi
kehidupannya di akhirat. Jika manusia berbuat baik di dunia, maka ia akan
menuai kebaikan pula kelak di akhirat. Sebaliknya, jika ia berbuat kejahatan di
dunia, maka kelak di akhirat ia akan mendapat celaka. Kedua, setiap orang harus
mengerahkan unsur dirinya, jasmani maupun rohani, kepada nasihat, petuah, dan
petunjuk Yang Mahakuasa untuk mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Tuhan.
Dan ketiga, paham kehidupan materialistis di dunia dapat berakibat buruk dalam
kehidupan manusia (Suriani, 2006). Dengan prinsip tallase kamasa-mase ini,
masyarakat adat Kajang diharapkan mampu mengekang hawa nafsunya, selalu
bersikap jujur, tegas, sabar, rendah hati, tidak melakukan perbuatan yang
merugikan orang lain, dan tidak memuja materi secara berlebihan.
Selain
ajaran tallase kamasa-mase, masyarakat adat Kajang juga memiliki
mekanisme lain untuk menjaga kelestarian hutan mereka, yaitu dengan cara
menetapkan kawasan hutan menjadi tiga bagian di mana setiap bagian memiliki
fungsi dan makna yang berbeda bagi masyarakat adat. Ketetapan ini langsung
dibuat oleh Ammatoa. Secara lebih jelas Al Rawali (2008) menyebutkan
tiga kawasan hutan tersebut sebagai berikut:
Kawasan yang
pertama adalah Barong Karamaka atau hutan keramat, yaitu kawasan hutan
yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, kecuali upacara-upacara adat.
Kawasan ini harus steril dari kegiatan penebangan, pengukuran luas, penanaman
pohon, pemanfaatan flora dan fauna yang ada di dalamnya, ataupun kunjungan
selain pelaksanaan upacara adat. Kawasan barong karamaka ini begitu
sakral bagi masyarakat Kajang karena adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah
tempat tinggal para leluhur orang Kajang. Hal ini diungkapkan secara jelas
dalam sebuah pasang, yaitu: “Talakullei nisambei kajua, Iyato’ minjo
kaju timboa. Talakullei nitambai nanikurangi borong karamaka. Kasipalli tauwa
a’lamung-lamung ri boronga, Nasaba’ se’re wattu la rie’ tau angngakui bate
lamunna” (Artinya: Tidak bisa diganti kayunya, itu saja kayu yang tumbuh.
Tidak bisa ditambah atau dikurangi hutan keramat itu. Orang dilarang menanam di
dalam hutan sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya.
Kawasan yang
kedua adalah Barong Batasayya atau hutan perbatasan. Hutan ini merupakan
hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada
dan dengan seizin dari Ammatoa selaku pemimpin adat. Jadi keputusan
akhir boleh tidaknya masyarakat mengambil kayu di hutan ini tergantung dari Ammatoa.
Pun kayu yang ada dalam hutan ini hanya diperbolehkan untuk membangun sarana
umum, dan bagi komunitas Ammatoa yang tidak mampu membangun rumah. Selain dari
tujuan itu, tidak akan diizinkan.
Namun, tidak
semua kayu boleh ditebang. Hanya beberapa jenis kayu saja yang boleh ditebang,
yaitu kayu Asa, Nyatoh, dan Pangi. Jumlah kayu yang ditebang pun harus sesuai
dengan kebutuhan, sehingga tidak jarang kayu yang ditebang akan dikurangi oleh
Ammatoa.
Syarat utama
ketika orang ingin menebang pohon adalah orang yang bersangkutan wajib menanam
pohon sebagai penggantinya. Kalau pohon itu sudah tumbuh dengan baik, maka
penebangan pohon baru dapat dilakukan. Menebang satu jenis pohon, maka orang
yang bersangkutan wajib menanam dua pohon yang sejenis di lokasi yang telah
ditentukan oleh Ammatoa. Penebangan pohon itu juga hanya boleh dilakukan
dengan menggunakan alat tradisional berupa kampak atau parang. Cara
mengeluarkan kayu yang sudah ditebang juga harus dengan cara digotong atau
dipanggul dan tidak boleh ditarik karena dapat merusak tumbuhan lain yang
berada di sekitarnya.
Dan kawasan
yang ketiga adalah Borong Luara’ atau hutan rakyat. Hutan ini merupakan
hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Meskipun kebanyakan hutan jenis ini
dikuasai oleh rakyat, namun aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan
ini tetap masih berlaku. Ammatoa melarang setiap praktek
kesewenang-wenangan dalam memanfaatkan sumberdaya yang terdapat dalam hutan
rakyat ini.
Agar ketiga
kawasan hutan tersebut tetap mampu memerankan fungsinya masing-masing, Ammatoa
akan memberikan sangsi kepada siapapun yang melanggar ketentuan yang telah
dibuatnya itu. Sangsi yang diberikan tidaklah sama, tergantung di kawasan hutan
mana orang yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan
di hutan keramat akan mendapatkan sanksi yang paling berat.
Pasang secara
eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan rusaknya
ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut
hasil-hasil hutan. Pasang inilah yang memberikan ketentuan tersebut agar
aturan yang ditetapkan berjalan dengan efektif. Konsekuensinya, bagi siapa saja
yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan akan dikenai sanksi yang
tegas. Tentang bagaimana usaha agar warga masyarakat menaati aturan pelestarian
hutan yang berdasarkan atas pasang, maka di bawah kepemimpinan Ammatoa
sebagai Kepala Adat Keammatoaan mengadakan acara abborong (bermusyawarah)
yang menetapkan bahwa pelanggaran atas ketentuan pasang yang berhubungan
dengan pelestarian hutan dikenakan denda (apabila diketahui pelanggarnya)
sebagai berikut:
Pertama, Cappa
Ba’bala atau pelanggaran ringan. Cappa Ba’bala diberlakukan terhadap
pelanggar yang menebang pohon dari koko atau kebun warga masyarakat adat
Ammatoa. Hukumannya berupa denda enam real atau menurut mata uang Indonesia
kira-kira setara dengan uang enam ratus ribu rupiah. Selain itu, pelanggar juga
wajib memberikan satu gulung kain putih kepada Ammatoa.
Kedua, Tangnga
Ba’bala atau pelanggaran sedang. Tangnga ba’bala merupakan sangsi
untuk pelanggaran yang dilakukan dalam kawasan hutan perbatasan atau Borong
Batasayya. Pengambilan kayu atau rotan atau apa saja dalam kawasan ini
tanpa seizin Ammatoa berarti melanggar aturan Tangnga ba’bala. Ketika
seseorang diizinkan oleh Ammatoa untuk mengambil sebatang pohon kemudian
ternyata mengambil lebih banyak dari yang diizinkan, maka orang tersebut telah
melanggar aturan Tangnga ba’bala ini. Denda dari pelanggaran ini
sebesar delapan real atau sebanding dengan delapan ratus ribu rupiah dengan
mata uang Indonesia ditambah satu gulung kain putih.
Ketiga, Poko’
Ba’bala atau pelanggaran berat. Poko’ ba’bala diberlakukan kepada
seluruh masyarakat yang bernaung di bawah kepemimpinan Ammatoa jika
melakukan pelanggaran berat menurut adat. Poko’ ba’bala diberlakukan
jika masyarakat adat melakukan pelanggaran di Barong maraka atau hutan
keramat dalam bentuk mengambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang
terdapat di dalamnya. Poko’ ba’bala merupakan hukuman terberat dalam
konsep aturan adat masyarakat Ammatoa. Masyarakat adat yang melakukan
pelanggaran berat dikenai sanksi berupa denda dua belas real, atau dalam mata
uang Indonesia setara dengan satu juta dua ratus ribu rupiah, kain putih satu
lembar, dan kayu yang diambil dikembalikan ke dalam hutan (Restu dan Sinohadji,
2008).
Di samping
sanksi berupa denda, hukuman adat yang sangat mempengaruhi kelestarian hutan
adalah sanksi sosial berupa pengucilan. Hukuman ini bagi masyarakat adat kajang
lebih menakutkan. Jika masyarakat melanggar Poko’ ba’bala maka Ammatoa
tidak akan menghadiri setiap acara atau pesta yang dilangsungkannya. Ketika Ammatoa
tidak hadir maka setiap acara atau pesta yang berlangsung dianggap sia-sia.
Bagi mereka yang telah melanggarnya, lebih baik dipenjara seumur hidup daripada
harus terkena Poko’ ba’bala. Lebih menakutkan lagi karena sanksi
pengucilan ini berlaku juga bagi seluruh keluarga sampai tujuh turunan.
Apabila
sebuah pelanggaran tidak diketahui siapa pelakunya, maka adat Ammatoa akan
melangsungkan upacara attunu panrolik (membakar linggis sampai merah karena
panasnya). Mendahului upacara tersebut dipukullah gendang di rumah Ammatoa
dengan irama tertentu yang langsung diketahui oleh warga masyarakat Keammatoaan,
bahwa mereka dipanggil berkumpul untuk menghadiri upacara attunu
panrolik. Kepada setiap warga masyarakat Keammatoaan dipersilakan
memegang linggis yang sudah berwarna merah karena panasnya. Bagi orang yang
tangannya melepuh ketika memegang linggis tersebut, maka dialah pelakunya.
Sedangkan bagi yang bukan pelaku, tidak akan merasakan panasnya linggis
tersebut. Akan tetapi pada umumnya pelaku tidak mau menghadiri upacara
tersebut, sehingga untuk mengetahui pelakunya (yang mutlak harus dicari), maka
diadakan upacara attunu passauk (membakar dupa) (Salle, 2000).
Mendahului
upacara tersebut, terlebih disampaikan pengumuman kepada segenap warga selama
sebulan berturut-turut, dengan harapan bahwa pelaku, maupun yang mengetahui
perbuatan penebangan pohon itu akan datang melapor kepada Ammatoa. Hal
itu sangat perlu, karena akibat dari attunu passauk yang sangat berat,
yaitu bukan hanya menimpa pelaku, akan tetapi juga kepada keturunannya. Attunu
passauk diadakan setelah attunu panrolik gagal menemukan pelaku.
Upacara dilakukan oleh Ammatoa bersama pemuka adat di dalam Barong
Karamaka. Attunu passauk adalah kegiatan menjatuhkan hukuman “in
absentia”. Hukuman ini dipercaya langsung diberikan oleh Turek Akrakna, yang
berupa musibah secara beruntun, baik pada pelaku, keluarga, dan keturunannya,
serta orang lain yang mengetahui perbuatan itu, namun tidak melaporkannya
kepada Ammatoa (Salle, 2000).
Namun, dalam
masyarakat Kajang sendiri, pemberlakukan denda dan sanksi bagi pelanggar
kelestarian hutan hanyalah sarana saja (bukan tujuan itu sendiri) karena
idealitas yang mereka kehendaki sebenarnya adalah terciptanya sebuah tatanan
masyarakat yang terbebas dari sanksi apapun. Sanksi dalam konteks ini berarti
hanya berfungsi sebagai sarana prevensi agar pelanggaran terhadap kelestarian
hutan dalam bentuk apapun tidak akan dilakukan oleh komunitas Ammatoa. Lantas,
apa kira-kira rasionalisasi dari pemberlakuan sanksi tersebut?
Bagi
masyarakat Kajang, hutan ibarat seorang ibu yang memberikan perlindungan
sekaligus harus dilindungi. Perumpamaan ini sebenarnya tidak hanya mengandung
makna filosofis saja, tetapi juga berimplikasi pada manfaat praktis terkait
dengan kegiatan-kegiatan pelestarian hutan. Terkait dengan hal ini, setidaknya
ada dua fungsi utama hutan bagi masyarakat Kajang. Pertama, sebagai fungsi
ritual yaitu salah satu mata rantai dari sistem kepercayaan yang memandang
hutan sebagai suatu yang sakral. Konsekuensi dari kepercayaan tersebut
tergambar pada upacara yang dilakukan dalam hutan, misalnya pelantikan pemimpin
adat (Ammatoa), attunu passaung (upacara kutukan bagi pelanggar adat),
upacara pelepasan nazar dan upacara angnganro (bermohon kepada Turek
Akrakna untuk suatu hajat baik individu maupun kolektif). Kedua, sebagai
fungsi ekologis, di mana hutan dipandang sebagai pengatur tata air (appariek
bosi, appariek tumbusu), yang menimbulkan adanya hujan dan menyimpan
cadangan air (Restu dan Sinohadji, 2008).
Kesimpulan
Penyebab
degradasi lingkungan adalah adanya pengeksploitasian sumberdaya alam oleh
manusia, baik oleh peme-rintah, perusahaan maupun masyarakat yang mempunyai
kepentingan dan akses tersendiri. Dengan demikian terjadi kon-testasi dan
konflik diantara mereka. Akibat dari kontestasi tersebut, menimbulkan
ketidakmerataan pendapatan ekonomi an-tara masyarakat local dengan
perusahaandan pemerintah. Ironisnya hasil dari sum-berdaya tersebut sebagian
besar masuk ke Negara Negara maju. Negara maju tinggal membayar, dan Negara
kita menghabisi sumberdayanya. Hal tersebut semakin meluas dari sabang sampai
merauke, sebab keberhasilan pembangunan dinilai dari pendapatan perkapita.
Dampak dari eks-ploitasi tersebut mengakibatkan bencana alam seperti banjir,
rusaknya hayati ke-lautan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam
pengeksploitasian sumberdaya alam, tidak bisa mengabaikan kearifan local, sebab
ke-arifan local berfungsi sebagai penyeimbang dan penyelaras lingkungan.
Demikian juga halnya dengan pengetahuan local yang selama ini dianggap tidak
ilmiah, tidak mempunyai metode, tetapi dalam penera-pannya bisa terbukti
keberadaannya dalam meminimalisir bencana sebagai akibat dari degradasi dan
fenomena
Sumber-sumber:
dari : Afthonul Afif,
Peneliti di BKPBM
Kredit foto:
Daftar
Pustaka
Adhan, S.,
2005, “Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir”, dalam
Hikmat Budiman, ed., Hak-Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di
Indonesia, Jakarta: Yayasan Interseksi bekerjasama dengan Tifa Foundation.
Al Rhawali,
A., Interaksi Manusia Adat Kajang dengan Lingkungannya, Diakses pada
Tanggal 29 Agustus 2008 dari http://alrawali.wordpress.com/berita-daerah/interaksi-manusia-adat-kajang-dengan-lingkungannya/
Azis, M., Pesan
Lestari dari Negeri Ammatoa, Diakses pada Tanggal 29 Agustus 2008 dari http://etalasehijau.blogspot.com/pesan-lestari-dari-negeri-ammatoa.html.
Restu, M.,
& Emil Sinohadji. Boronga ri Kajang (Hutan di Kajang). Diakses pada
Tanggal 29 Agutus 2008 dari http://www.fkkm.org/PusatData/index.php?action=detail3&page=22&lang=ind
Rossler, M.,
1990, “Striving for modesty; Fundamentals of the religion and social
organization of the Makassarese Patuntung”, In: Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde 146 (1990), no: 2/3, Leiden, 289-324. Diakses dari http://www.kitlv-journals.nl/files/pdf/art_BKI_1393.pdf
Salle, K,
2000, “Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang: Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat
pada Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Daerah Tingkat II
Bulukumba”, dalam Jurnal Pascasarjana Universitas hasanuddin Vol. 1 Thn. 2000.
Diakses dari http://www.pascaunhas.net/jurnal_pdf/vol_1_2/kaimud.pdf
Suriani,
2006, “Tanah Laksana Ibu bagi Suku Kajang”, dalam Harian Sore Sinar Harapan Edisi
06 Februari 2006.
Usop, KMA.
M. 1985. Pasang ri Kajang:Kajian Sistem Nilai Masyarakat Amma Toa dalam
Agama dan Realitas Sosial. Diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-ilmu Sosial,
Hasanuddin University Press.
Widyasmoro,
T.T., 2006, “Kajang, Badui dari Sulawesi”, dalam Majalah Intisari Edisi:
No. 511 TH.XLIII Februari 2006. Diakses dari http://www.intisari-online.com
KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN LOKAL DAN DEGRADASI
LINGKUNGAN
Erwan BaharudinFakultas Ilmu Komunikasi – Universitas Esa Unggul, Jakarta
Daftar Pustaka
Agrawal, A, “Indegeneous and Scientific
Knowledge: Some Critical
Comments.Indigeneous
Knowledge and Development Monitor”, 3 (3) : 3-6. 1995.
Amalamien, “Penelitian Ilmiah Berbasis Pengetahuan Lokal”, 2008.
Berbagai Sumber
Knowledge: Some Critical
Comments.Indigeneous
Knowledge and Development Monitor”, 3 (3) : 3-6. 1995.
Amalamien, “Penelitian Ilmiah Berbasis Pengetahuan Lokal”, 2008.
Berbagai Sumber
Bryant, Raymond L, Sinead Bailey, “Third World Political
Ecology”, Routledge, New York, 1997.
Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan”, LP3ES,
Jakarta, 1993.
Hans J. Daeng, “Manusia, Kebudayaan dan
Lingkungan Tinjauan Antropologis” ,Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2008.
Hari Poerwanto, “Kebudayaan dan lingkungan dalam
Perspektif Antro-pologi”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
Herbert Marcuse, “One Dimensional Man: Studies in
Ideology of Advanced Industrial Society”, Routledge, New York, 2002.
Johan Iskandar, “Mitigasi Bencana Lewat Kearifan
Lokal”, Kompas, 6 Oktober 2009.
Lester R, Brown, “Tantangan Masalah Lingkungan Hidup
Bagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdasarkan Kesinambungan Lingkungan
Hidup yang Sehat”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
Lowe, Celia, “Wild Profusion: Biodiversity Conservation in an Indonesian Archipelago”, Princeton University Press. Sub-topik The Reason for Reason hal: 19-23, 2006.
Lowe, Celia, “Wild Profusion: Biodiversity Conservation in an Indonesian Archipelago”, Princeton University Press. Sub-topik The Reason for Reason hal: 19-23, 2006.
Nygren, A, “Local Knowledge in the
Environment-Development Discourse: From Dicotomies to Situated Knowledge”,
Critique of Anthropology 19 (3): 267-288, 1999.
Watts, M, Chapter 16. Political Ecology, in Eric
Sheppard and Trevor J. Barnes [eds.], A Companion to Economic Geography.
Oxford: Blackwell Publisher Ltd. sub-topik tentang knowledge, power, practice
halaman 263-265, 2003.


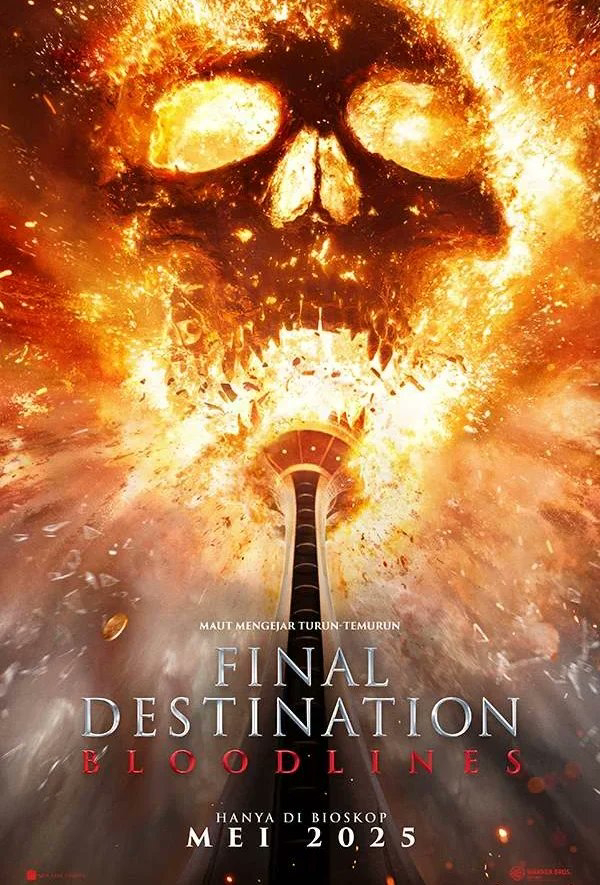

Comments
Post a Comment