Isu Perbatasan Sabah–Kalimantan: Meluruskan Fakta di Tengah Riuh Narasi Kehilangan Kedaulatan
Sejak semalam, ruang publik—khususnya media sosial—diramaikan oleh narasi bahwa kedaulatan negara “tergadai”. Isunya terdengar serius: disebutkan bahwa Malaysia telah “menyerahkan” sekitar 5.207 hektare tanah di kawasan perbatasan Sabah–Kalimantan (Nunukan) kepada Indonesia.
Bagi masyarakat awam, angka ribuan hektare tentu terdengar besar. Narasi kehilangan wilayah pun mudah memicu emosi, kecurigaan, bahkan kemarahan. Namun, sebelum kesimpulan ditarik terlalu jauh, penting untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat persoalan ini secara utuh dan jernih.
Apa sebenarnya yang terjadi?
Isu ini bukan soal jual beli tanah, bukan pula hadiah wilayah antarnegara. Persoalan yang dimaksud adalah Outstanding Boundary Problems (OBP), yakni persoalan batas wilayah yang sejak masa kolonial belum memiliki penegasan garis perbatasan yang jelas di lapangan.
Perjanjian-perjanjian lama antara Inggris dan Belanda—khususnya perjanjian tahun 1915 dan 1928—memang telah menetapkan prinsip batas wilayah. Namun, keterbatasan teknologi pengukuran pada masa itu membuat sejumlah segmen perbatasan hanya digambar secara kasar di peta, tanpa koordinat yang presisi.
Baru di era modern, dengan teknologi pemetaan dan survei geospasial yang jauh lebih akurat, garis batas tersebut dapat diukur kembali sesuai dengan dokumen perjanjian internasional yang telah disepakati sejak lebih dari seabad lalu.
Bagaimana hasil pengukurannya?
Di kawasan Sungai Sinapat dan Sungai Sesai, luas wilayah yang selama ini dianggap “diperselisihkan” mencapai sekitar 5.987 hektare. Pengukuran ulang dilakukan berdasarkan prinsip watershed (alur daerah aliran sungai) serta garis lintang 4°20′, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kolonial.
Hasilnya sebagai berikut:
Sekitar 780 hektare wilayah yang aliran airnya mengarah ke utara secara sah ditetapkan sebagai bagian dari Malaysia.
Sementara 5.207 hektare lainnya berada di selatan garis batas tersebut dan secara hukum internasional memang termasuk wilayah Indonesia.
Dengan kata lain, tidak ada wilayah yang “dipindahkan” atau “diserahkan”. Yang terjadi adalah penegasan atas garis batas yang sejak awal sudah disepakati, tetapi belum pernah ditetapkan secara teknis dan final.
Apakah ada pihak yang dirugikan?
Secara hukum dan faktual, tidak. Wilayah seluas 5.207 hektare tersebut sejak awal memang berada dalam klaim Indonesia berdasarkan perjanjian Inggris–Belanda. Penetapan terbaru hanya mengukuhkan status yang telah ada, bukan menciptakan kepemilikan baru.
Bahkan, Malaysia justru memperoleh kepastian hukum atas sekitar 780 hektare wilayah yang sebelumnya berada dalam status abu-abu. Dari sudut pandang diplomasi dan hukum internasional, kejelasan batas ini justru mengurangi potensi konflik di masa depan.
Lalu, mengapa isu ini menjadi gaduh?
Sebagian kegaduhan muncul dari penyederhanaan berlebihan, bahkan pemelintiran fakta. Narasi “tanah negara tergadai” memang efektif membakar emosi publik, terutama di tengah iklim politik yang sensitif. Padahal, proses perundingan batas wilayah ini telah berlangsung lintas pemerintahan dan selalu berpijak pada perjanjian internasional yang sama.
Isu perbatasan adalah persoalan teknis, hukum, dan diplomasi—bukan transaksi dagang, apalagi pengkhianatan kedaulatan. Tidak ada satu inci pun wilayah yang “hilang” dari apa yang secara hukum memang menjadi hak negara.
Di era media sosial, judul sensasional sering kali bergerak lebih cepat daripada fakta. Karena itu, kehati-hatian dalam menyerap informasi menjadi kunci. Tidak semua kabar yang viral mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.
Dalam kasus perbatasan Sabah–Kalimantan ini, kedaulatan negara tetap terjaga. Yang terjadi bukan kehilangan wilayah, melainkan penegasan batas demi kepastian hukum dan stabilitas hubungan antarnegara.



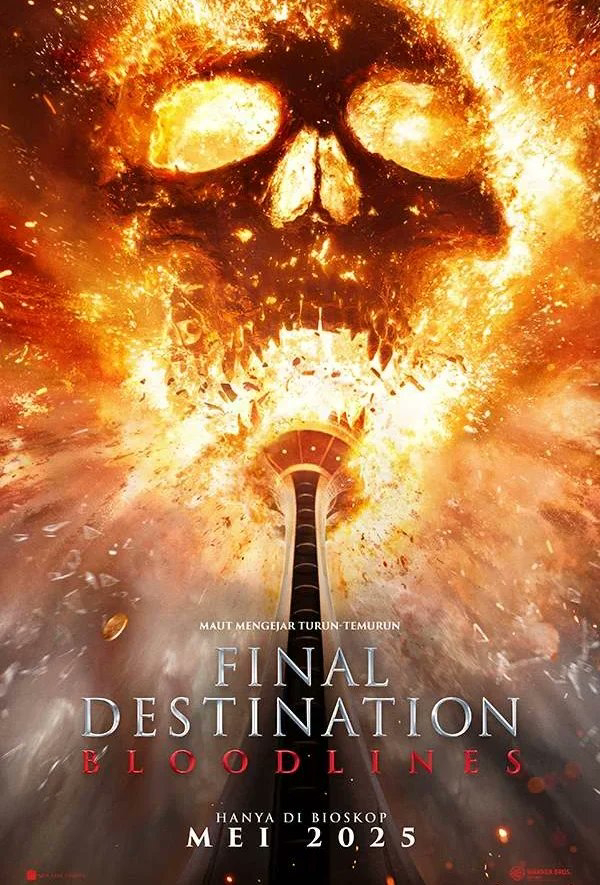
Comments
Post a Comment