Mengapa Generasi Dulu Banyak Disebut “People Pleaser”?
Bukan karena mereka lemah.
Melainkan karena itulah cara yang diajarkan kepada mereka untuk bertahan hidup.
Sejak kecil, banyak dari generasi sebelumnya dibesarkan untuk patuh, bukan untuk bersuara. Menjaga perasaan orang lain dianggap lebih penting daripada menjaga perasaan diri sendiri. Mengalah dipandang sebagai kedewasaan. Sementara melawan sering dilabeli sebagai tidak sopan.
Ketika masuk ke dunia kerja, pola ini semakin menguat. Struktur organisasi kaku, peluang terbatas. Mengatakan “iya” terasa lebih aman. Mengatakan “tidak” bisa berisiko—pada karier, penghasilan, bahkan relasi kerja.
Lama-kelamaan, mengikuti kehendak orang lain menjadi kebiasaan.
Namun ini bukan semata-mata soal people pleasing. Ini tentang keterampilan sosial dalam hidup bermasyarakat.
Manusia hidup dalam komunitas. Kita saling membutuhkan dan saling bergantung. Banyak Millennials sebenarnya bukan people pleaser, melainkan pandai menjaga hubungan.
Ya, terkadang tidak bahagia.
Namun dari sanalah banyak dari kami membangun mental yang lebih tahan banting.
Di sisi lain, generasi yang lebih muda hari ini jauh lebih berani berkata “TIDAK”—dan itu baik. Namun bersamaan dengan itu, angka kecemasan dan depresi juga semakin tinggi. Ironisnya, meski sering berkata “tidak”, mereka hidup dalam tekanan FOMO yang konstan.
Bagi saya, persoalannya bukan tentang YA atau TIDAK. Tetapi kapan, bagaimana, dan untuk apa kata itu diucapkan.
Sebagai seorang Millennial (Y2K), saya percaya: Selama situasi masih terkendali dan emosi masih bisa dikelola, bersikap diplomatis adalah bentuk kedewasaan—bukan kelemahan.
Mengatakan “tidak” bukan tiket untuk terlihat berani. Dan mengatakan “iya” bukan selalu tanda ketidakberdayaan.
Kematangan sejati adalah mengetahui waktu yang tepat untuk bersuara, serta kebijaksanaan menjaga relasi tanpa kehilangan diri sendiri.
Jadi, apakah kita sedang membesarkan generasi yang lebih berani—atau generasi yang semakin lelah?

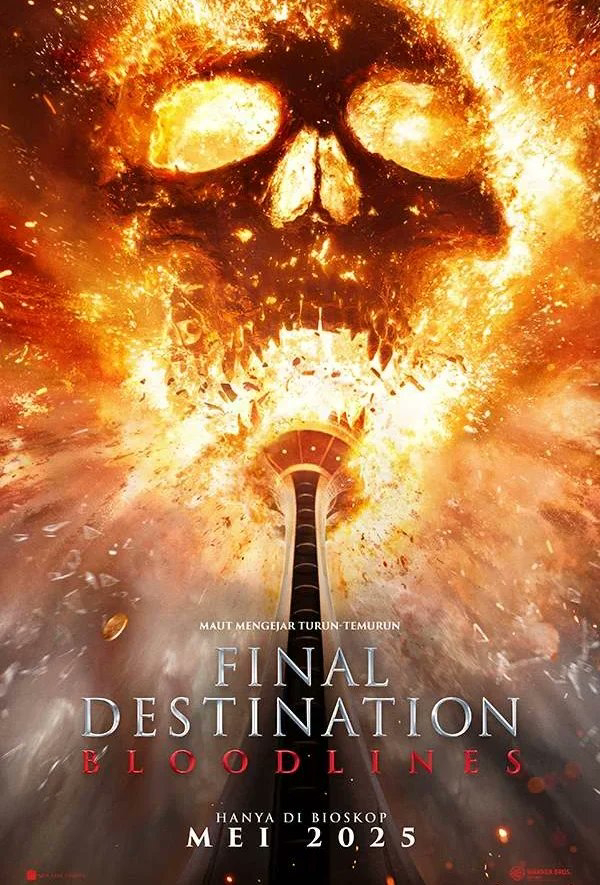

Comments
Post a Comment