SENGGOLAN
SENGGOLAN
Ustadz Muhsin Labib
Deru klakson memekakkan telinga, asap knalpot menyesakkan dada, dan di antara jalinan besi dan aspal yang tak berujung, kita hidup. Pagi ini, dalam perjalanan menuju kampus, ironi kekerasan Ibu Kota kembali menampakkan wajahnya.
Bukan baku hantam, bukan pula amukan massa, melainkan sentuhan sepele yang menguak retaknya kesabaran dan menelanjangi individualisme yang kian membudaya.
Motor yang membonceng saya menyenggol mobil yang tiba-tiba berbelok.
Insiden kecil, begitu sepele. Namun, di tengah kepungan kendaraan yang berdesakan, di bawah tatapan lampu lalu lintas yang tak sabar, sebuah drama mini pun terhampar.
Si empunya mobil menepi, lebih memikirkan goresan pada bodi kendaraannya daripada keselamatan manusia yang baru saja disentuhnya.
Kami pun menepi, bukan karena khawatir, melainkan demi menghindari sumpah serapah klakson dan tatapan kesal para pengendara
di belakang yg tak sudi kemacetan bertambah.
Mobil menepi, pengemudi bergegas turun dg wajah tegang, menyusuri bodi mobilnya, mencari-cari tanda kerusakan.
Matanya menyapu setiap lekukan, setiap inci cat yang mengkilap. Sementara itu, kami—dengan motor keluaran 2015 yang sudah dekil, penuh goresan dan penyok dari berbagai "pertempuran" jalanan—hanya bisa menunggu. Tak ada kekhawatiran berarti di pihak kami.
Lecet atau penyok baru pada motor tua ini hanyalah tambahan dari koleksi luka-luka yang sudah ada.
Detik-detik berlalu. Raut wajah sang pengemudi, yang tadinya sangar dan penuh perhitungan, perlahan melunak. Ia tidak menemukan goresan.
Tidak ada lecet. Mobilnya, yang mungkin bagi sebagian orang adalah simbol status dan hasil jerih payah, ternyata masih sempurna. Ekspresi lega menyeruak, menggantikan ketegangan sebelumnya.
Bagi kami, ini adalah ironi yang jelas: kekhawatiran terhadap materi jauh lebih besar daripada interaksi antarmanusia. Mobilnya aman, dan itu cukup.
Ini bukan lagi tentang emosi yang meledak-ledak. Ini adalah kekerasan terselubung, hasil dari tekanan ekonomi yang kian memburuk.
Setiap detik di jalan adalah perhitungan rugi-laba: telat sedikit berarti kehilangan penghasilan, atau setidaknya, kehilangan jatah waktu yang berharga. Mobil adalah investasi, motor adalah alat perjuangan.
Goresan kecil bukan sekadar lecet, tapi potensi biaya tak terduga yang bisa mengikis tipisnya tabungan.
Dalam kondisi seperti ini, siapa yang bisa menyalahkan sang pengemudi mobil? Atau kami yang buru-buru mengejar celah? Semua adalah korban dari sistem yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan, pada akhirnya, individualisme.
Kita didorong untuk fokus pada diri sendiri, pada tujuan kita sendiri, bahkan jika itu berarti mengabaikan sejenak rasa kemanusiaan.
Individualisme ini membudaya, meresap hingga ke pori-pori.
Di antara gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan megah, koneksi antarmanusia seringkali terputus. Kita hidup berdampingan, namun seringkali terpisah oleh sekat-sekat kepentingan pribadi.
Insiden kecil di jalanan adalah cerminan dari fenomena ini. Empati menjadi barang mewah, dan setiap orang sibuk dengan perjuangannya sendiri.
Kita terpaksa menjadi predator dan mangsa dalam ekosistem perkotaan yang brutal.
Mengambil hak jalan, memotong antrean
dg prinsip "masuk kepala, berhak ngegas", atau sekadar enggan mengalah meski bbrpa detik. Semua itu adalah fitur kekerasan pasif yg terus-menerus terjadi. Bukan karena niat jahat, melainkan karena dorongan untuk bertahan, utk mencapai tujuan.
Kisah pagi ini hanyalah sekelumit dari realitas keras Ibu Kota. Di balik hiruk pikuk dan kemegahan, tersembunyi ironi kekerasan yang tak berdarah, namun menggerogoti esensi kemanusiaan kita.
Kita telah banyak kehilangan etika sosial, rasa hormat, dan solidaritas.
Lama-lama, kita bukan hidup bersama—tapi saling sikut untuk selamat sendiri.
Ini semua akibat kita dididik oleh lingkungan yang mengagungkan kecepatan, hasil, dan ego, tapi lupa menanamkan empati, kesabaran, dan tata krama.
Kita hidup dalam sistem yang membuat menang lebih penting daripada benar,
dan selamat sendiri lebih penting daripada selamat bersama.
Jadi jangan heran, jika yang tumbuh bukan masyarakat—tapi kerumunan ego yang berlomba jadi paling duluan.
Ustadz Muhsin Labib
Deru klakson memekakkan telinga, asap knalpot menyesakkan dada, dan di antara jalinan besi dan aspal yang tak berujung, kita hidup. Pagi ini, dalam perjalanan menuju kampus, ironi kekerasan Ibu Kota kembali menampakkan wajahnya.
Bukan baku hantam, bukan pula amukan massa, melainkan sentuhan sepele yang menguak retaknya kesabaran dan menelanjangi individualisme yang kian membudaya.
Motor yang membonceng saya menyenggol mobil yang tiba-tiba berbelok.
Insiden kecil, begitu sepele. Namun, di tengah kepungan kendaraan yang berdesakan, di bawah tatapan lampu lalu lintas yang tak sabar, sebuah drama mini pun terhampar.
Si empunya mobil menepi, lebih memikirkan goresan pada bodi kendaraannya daripada keselamatan manusia yang baru saja disentuhnya.
Kami pun menepi, bukan karena khawatir, melainkan demi menghindari sumpah serapah klakson dan tatapan kesal para pengendara
di belakang yg tak sudi kemacetan bertambah.
Mobil menepi, pengemudi bergegas turun dg wajah tegang, menyusuri bodi mobilnya, mencari-cari tanda kerusakan.
Matanya menyapu setiap lekukan, setiap inci cat yang mengkilap. Sementara itu, kami—dengan motor keluaran 2015 yang sudah dekil, penuh goresan dan penyok dari berbagai "pertempuran" jalanan—hanya bisa menunggu. Tak ada kekhawatiran berarti di pihak kami.
Lecet atau penyok baru pada motor tua ini hanyalah tambahan dari koleksi luka-luka yang sudah ada.
Detik-detik berlalu. Raut wajah sang pengemudi, yang tadinya sangar dan penuh perhitungan, perlahan melunak. Ia tidak menemukan goresan.
Tidak ada lecet. Mobilnya, yang mungkin bagi sebagian orang adalah simbol status dan hasil jerih payah, ternyata masih sempurna. Ekspresi lega menyeruak, menggantikan ketegangan sebelumnya.
Bagi kami, ini adalah ironi yang jelas: kekhawatiran terhadap materi jauh lebih besar daripada interaksi antarmanusia. Mobilnya aman, dan itu cukup.
Ini bukan lagi tentang emosi yang meledak-ledak. Ini adalah kekerasan terselubung, hasil dari tekanan ekonomi yang kian memburuk.
Setiap detik di jalan adalah perhitungan rugi-laba: telat sedikit berarti kehilangan penghasilan, atau setidaknya, kehilangan jatah waktu yang berharga. Mobil adalah investasi, motor adalah alat perjuangan.
Goresan kecil bukan sekadar lecet, tapi potensi biaya tak terduga yang bisa mengikis tipisnya tabungan.
Dalam kondisi seperti ini, siapa yang bisa menyalahkan sang pengemudi mobil? Atau kami yang buru-buru mengejar celah? Semua adalah korban dari sistem yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan, pada akhirnya, individualisme.
Kita didorong untuk fokus pada diri sendiri, pada tujuan kita sendiri, bahkan jika itu berarti mengabaikan sejenak rasa kemanusiaan.
Individualisme ini membudaya, meresap hingga ke pori-pori.
Di antara gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan megah, koneksi antarmanusia seringkali terputus. Kita hidup berdampingan, namun seringkali terpisah oleh sekat-sekat kepentingan pribadi.
Insiden kecil di jalanan adalah cerminan dari fenomena ini. Empati menjadi barang mewah, dan setiap orang sibuk dengan perjuangannya sendiri.
Kita terpaksa menjadi predator dan mangsa dalam ekosistem perkotaan yang brutal.
Mengambil hak jalan, memotong antrean
dg prinsip "masuk kepala, berhak ngegas", atau sekadar enggan mengalah meski bbrpa detik. Semua itu adalah fitur kekerasan pasif yg terus-menerus terjadi. Bukan karena niat jahat, melainkan karena dorongan untuk bertahan, utk mencapai tujuan.
Kisah pagi ini hanyalah sekelumit dari realitas keras Ibu Kota. Di balik hiruk pikuk dan kemegahan, tersembunyi ironi kekerasan yang tak berdarah, namun menggerogoti esensi kemanusiaan kita.
Kita telah banyak kehilangan etika sosial, rasa hormat, dan solidaritas.
Lama-lama, kita bukan hidup bersama—tapi saling sikut untuk selamat sendiri.
Ini semua akibat kita dididik oleh lingkungan yang mengagungkan kecepatan, hasil, dan ego, tapi lupa menanamkan empati, kesabaran, dan tata krama.
Kita hidup dalam sistem yang membuat menang lebih penting daripada benar,
dan selamat sendiri lebih penting daripada selamat bersama.
Jadi jangan heran, jika yang tumbuh bukan masyarakat—tapi kerumunan ego yang berlomba jadi paling duluan.


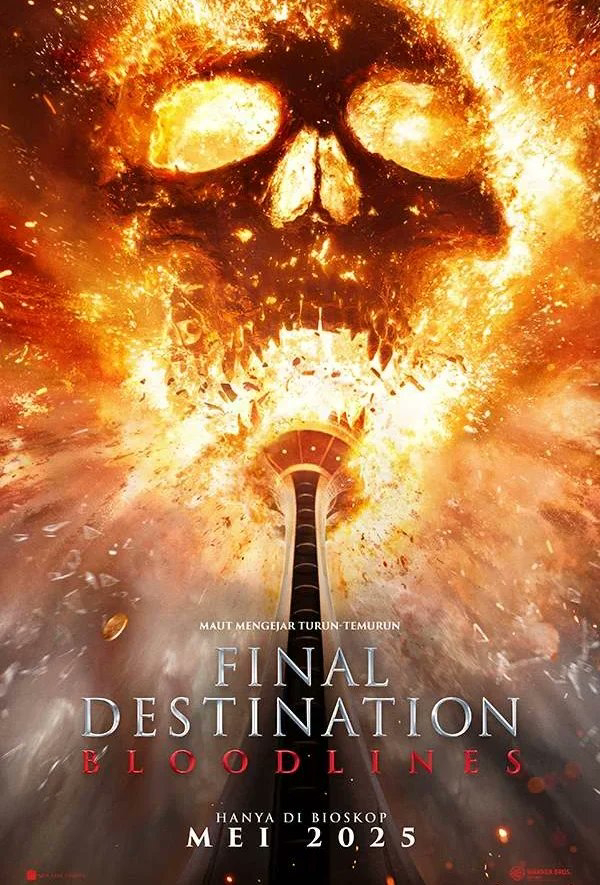
Comments
Post a Comment