BILA ASU IKUT MENYERANG, Credit : Labib Muhsin
Presiden ASU bilang sedang mempelajari kemungkinan melibatkan diri dalam menyerang reaktor-reaktor nuklir.
Ada kebutaan fatal dalam kalkulus politik Donald Trump—sebuah ketidakpekaan terhadap denyut nadi peradaban kuno. Ia memandang Iran sebagai entitas rapuh yang akan runtuh di bawah tekanan sanksi dan ancaman, tanpa menyadari bahwa di balik struktur pemerintahan modernnya, mengalir darah kebangsaan yang telah berusia dua milenium.
Yang luput dari pandangannya adalah esensi bangsa berperadaban agung: mereka tidak sekadar mempertahankan sebuah rezim, melainkan menjaga identitas yang terpahat pada prasasti Persepolis dan terucap dalam bait-bait Hafez. Serangan dari Amerika Serikat atau Israel—terlebih jika dilakukan serentak—tidak akan mematahkan Teheran, melainkan menjadi anugerah tak terduga bagi Republik Islam, mengukuhkan pemerintahannya sebagai benteng kedaulatan yang tak tergoyahkan.
Ironi yang pedih terletak di sini: agresi yang dimaksudkan untuk memecah Iran justru merajut tapestri persatuan nasional yang sebelumnya retak. Oposisi di pengasingan, yang biasanya lantang mengutuk kebijakan domestik, tiba-tiba terdiam ketika rudal asing mengoyak tanah air mereka. Mereka tidak membela ideologi tertentu, melainkan martabat bangsa yang diinjak oleh sepatu lars asing.
Nasionalisme Persia yang membara menenggelamkan sementara dendam politik. Bagi pemerintah di Teheran, ini adalah legitimasi yang datang bagaikan kilat: dari penguasa yang dituduh menindas, mereka menjelma menjadi pelindung tanah leluhur dalam semalam. Krisis ekonomi dan gemuruh protes domestik sirna, digantikan oleh retorika heroik melawan musuh bersama.
Lebih jauh, serangan terhadap Iran akan menyulut solidaritas yang melampaui batas nasional, mengguncang lanskap geopolitik dengan kekuatan yang belum pernah terbayangkan. Sekitar 600 juta umat Muslim Syiah di seluruh dunia, yang sebagian besar bertaqlid kepada figur otoritatif seperti Sayyid Ali Khamenei dan Sayyid Ali al-Sistani, akan bersatu menjadi kekuatan kolektif yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Dari Irak hingga Lebanon, dari Bahrain hingga Pakistan, komunitas Syiah yang selama ini terfragmentasi oleh dinamika lokal akan menemukan tujuan bersama dalam membela Iran sebagai simbol perlawanan. Persatuan ini, yang dipicu oleh agresi asing, bukan hanya akan memperkuat posisi Teheran, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan global, menciptakan front ideologis dan militer yang tak tertandingi.
Di samping ikatan keagamaan ini, serangan tersebut juga akan membangkitkan solidaritas etnis yang kuat di antara semua etnis Persia yang tersebar di sejumlah negara seperti Iran sendiri, Azerbaijan, Uzbekistan, Bahrain (yang dulu merupakan bagian dari Iran), juga seperempat dari penduduk Turki dan sejumlah negara Teluk terutama Irak dan Uni Emirat Arab, yang akan tersulut oleh sentimen etnis yang cukup luas. Di Azerbaijan dan Uzbekistan, serangan ini akan membangkitkan loyalitas leluhur yang mendalam terhadap tanah air Persia mereka. Bahrain, dengan ikatan sejarahnya sebagai bagian dari Iran, akan menyaksikan komunitas Persia-nya bergolak dalam semangat pembelaan. Di Turki, di mana seperempat penduduk memiliki akar Persia, dan di Irak serta UEA, di mana minoritas Persia menjaga hubungan budaya yang erat dengan Iran, agresi ini akan bergema sebagai panggilan untuk melindungi identitas bersama. Kebangkitan etnis ini dapat terwujud dalam demonstrasi massal, tekanan politik terhadap pemerintah lokal, hingga dukungan nyata bagi Iran, memperumit situasi geopolitik lebih jauh.
Persatuan menuntut harga yang mengerikan: pintu menuju kekacauan global terbuka lebar. Iran bukan pulau terpencil di lautan geopolitik. Serangan terhadapnya akan memicu reaksi berantai yang mengguncang tatanan dunia. Selat Hormuz akan menjadi makam kapal-kapal dagang. Rudal hipersonik dan drone akan melesat melintasi perbatasan, sementara serangan siber melumpuhkan pusat-pusat keuangan di London dan New York. Sekutu-sekutu Iran, dari Beirut hingga Sana’a, akan bangkit membalas.
Bila Amerika Serikat ikut menyerang, maka bagi Iran sasarannya lebih dekat dan tidak memerlukan akurasi tinggi karena serangan acak saja sudah cukup untuk membakar pangkalan militer AS di negara-negara mini Teluk. Setiap terminal minyak, pusat data, dan bandara internasional berpotensi menjadi medan tempur. Frasa “setiap titik di jagat jadi arena perang” bukanlah kiasan puitis—ia adalah nubuat yang terukir dalam bahasa realpolitik abad ke-21.
Menyederhanakan Iran sebagai “negara teroris” adalah pelecehan terhadap jiwa bangsa yang pernah menahan gempuran Aleksander Agung, bangkit dari abu invasi Mongol, dan bertahan dalam perang delapan tahun melawan Saddam Hussein. Pemerintah Teheran memahami naluri ini jauh lebih dalam ketimbang para penasihat Gedung Putih: dalam cawan konflik, kepahitan rakyat terhadap penguasa akan mengkristal menjadi solidaritas melawan agresor. Serangan asing mengubah kalkulasi oposisi menjadi puisi perlawanan kuno: “Jika musuh datang menjarah, tanah leluhur ini akan kami pertahankan dengan permadani anyaman darah mereka.”
Akhir dari tragedia ini telah terbaca jelas: pemerintah Iran memanen kekuatan dari api perang yang dinyalakan musuhnya sendiri, sementara dunia menanggung beban kehancuran. Trump mungkin memimpikan kemenangan kilat, bak transaksi bisnis yang ditandatangani di menara emasnya, tetapi sejarah berbisik dengan nada sinis: bangsa dengan memori peradaban panjang tidak pernah ditundukkan oleh kekerasan semata. Mereka justru semakin kokoh dalam menghadapinya. Ketika debu perang mengendap, Iran tidak akan remuk. Ia akan menjulang, dengan bendera yang kini dikibarkan bahkan oleh mereka yang dulu menentangnya—sebuah peradaban agung yang bangkit dari bayangan kemenangan musuhnya

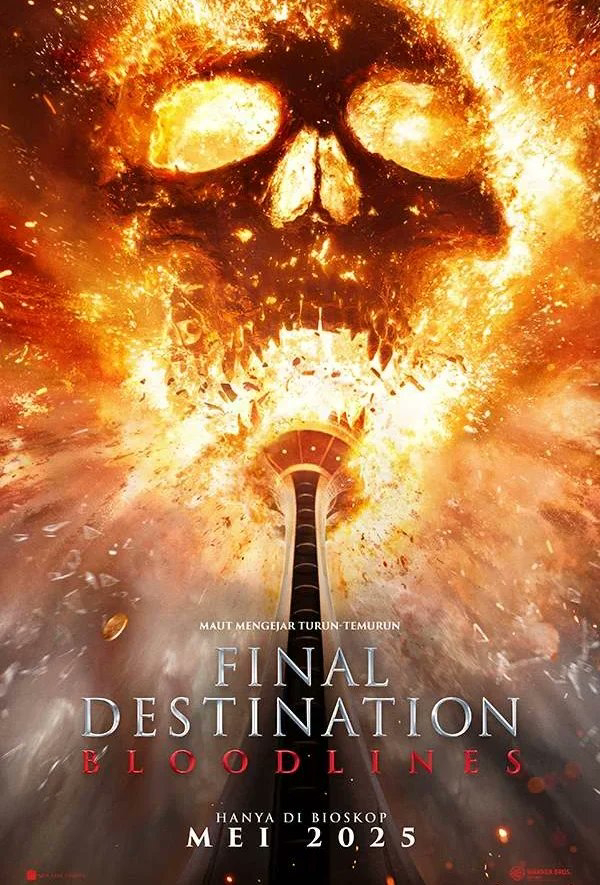

Comments
Post a Comment